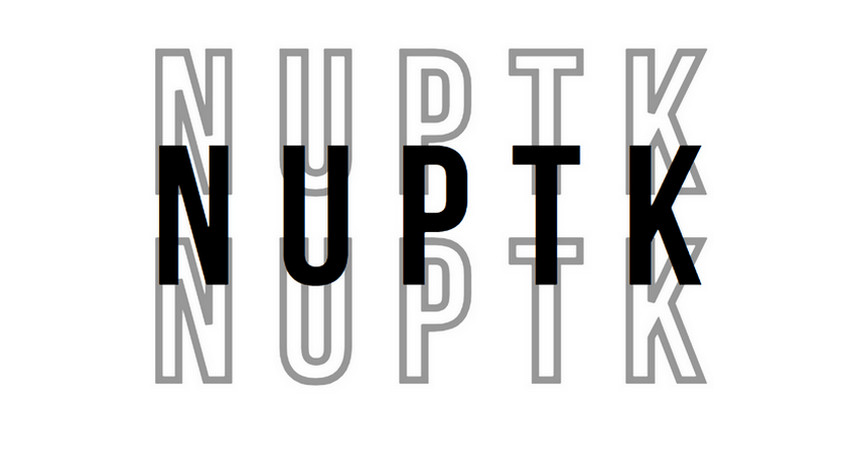Jelang akhir Desember tiap tahun, pertanyaan klise “bolehkah umat Islam mengucapkan Selamat Natal kepada umat Nasrani?” berseliweran di media sosial. Jawabannya beragam, meski dominasi jawaban di media sosial bisa ditebak yakni tidak boleh. Dan banyak sekali penjelasan yang turut menyertainya.
Namun, tulisan singkat ini tidak dalam rangka menjelaskan boleh atau tidak boleh. Tidak juga dalam rangka mengajukan dasar-dasar biblis untuk memperkuat salah satu jawaban. Apalagi menegasi pertanyaan tersebut. Tulisan singkat ini ingin mengajak kita untuk mempertanyakan hal yang lebih mendasar dan urgen untuk dijawab.“Bolehkah kita hidup bersama sebagai saudara?”
Kita seharusnya lebih konsen untuk menjawab pertanyaan ini. Realitas sosial saat ini sangat butuh jawaban kita, mengingat setiap hari kita dihadapkan kepada berbagai macam orang dengan beragam latar belakang. Pun, ruang lingkup jawaban atas pertanyaan ini bukan hanya ranah agama saja, melainkan juga ranah kultur, sosial, geografis, bahkan psikologis.
Kita butuh jawaban atas pertanyaan ini dari berbagai penjuru Indonesia. Yang di barat Indonesia tentu memberi jawaban berdasarkan realitas sosio-kulturalnya. Yang di timur Indonesia akan menghadirkan jawaban berdasarkan kenyataan hidup bersama yang mereka rajut selama ini. Demikian pula dengan saudara-saudari kita di utara dan selatan. Jawaban-jawaban itulah yang kemudian merangkai satu suara untuk Indonesia.
Dengan demikian diskusi kita tidak hanya bergerak di satu tempat dan berputar-putar di situ saja, melainkan bergerak maju sesuai dengan tuntutan global. Pertanyaan “bolehkan mengucapkan selamat natal” adalah pertanyaan retorik yang diajukan hanya untuk mempolarisasi atau memecah belah. Dalam pandangan saya, pertanyaan ini justru dikemukakan untuk memperuncing perbedaan dan memperlebar dikotomi di antara kita.
Daripada memecah belah, bagaimana kalau kita alihkan fokus kepada pertanyaan yang membawa rasa teduh dan solutif untuk berbagai perbedaan kita. Seperti, dapatkah kita hidup bersama dalam keberagaman ini? Apakah persaudaraan universal dapat kita capai dalam aneka perbedaan ini?
Mundur ke belakang, sebetulnya ini bukan hal baru. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah kita temukan jejak-jejaknya dalam lintasan sejarah bangsa Indonesia. Para pendiri bangsa kita sadar betul bahwa Indonesia yang secara geografis terdiri dari ribuan pulau dengan masing-masing kultur dan agama ini tidak mungkin dibangun atas dasar satu agama, budaya, atau satu suku saja. Ia harus dirajut dari benang-benang perbedaan agar terangkai satu ayaman yang indah.
Perbedaan justru dipandang sebagai kekayaan sekaligus kekuatan bangsa Indonesia untuk menawarkan perspektif alternatif kepada dunia bahwa bangsa ini dapat hidup bersama dan rukun dalam berbagai keragaman. Kita mampu tumbuh bersama dalam aneka perbedaan. Identitas kita adalah keragaman, bukan keseragaman apalagi pemisahan.
Maka tidak salah kalau Pancasila kemudian diletakkan sebagai falsafah bangsa yang dapat menyatukan perbedaan-perbedaan itu. Lima sila tersebut ditempatkan dalam salah satu tarikan nafas yakni nafas kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, diskursus kita hari ini haruslah berpijak pada falsafah ini. Pancasila mesti menjadi inspirasi sekaligus petunjuk untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi.
Tatkala perbedaan dipandang sebagai daya pemisah, maka ujungnya adalah perpecahan dan saling benci. Padahal, perbedaan seharusnya menjadi sumbu bagi timbulnya sinar persaudaraan dan kerukunan. Sehingga kita dapat melangkah bersama sebagai bangsa dan negara hingga bertahun-tahun yang akan datang.
Sebagaimana diuraikan oleh tokoh Islam ternama, Ahmad Syafii Maarif dalam bukunya “Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan”. Dalam salah satu bagian ia menulis, jika kita dapat bertahan sebagai sebuah bangsa dan negara yang utuh dan berdaulat penuh dalam rentang waktu yang tak terbatas, sungguh merupakan anugerah Allah yang sangat tinggi nilainya.
“Ke arah itulah kita harus melangkah dengan membuang egoisme sub-kultur, parokialisme, kepongahan daerah, kepentingan sesaat, dan pragmatisme politik yang tunanilai. Harus senantiasa diingat bahwa bangsa ini terlalu besar dan mahal untuk dikorbankan demi meraih tujuan-tujuan rendahan sesaat.”
Maka, saya berharap di waktu yang akan datang pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan lebih kritis dan punya daya dobrak agar membangkitkan kesadaran untuk bergerak bersama sebagai sebuah bangsa kepada tujuan yang luhur dan mulia. Sembari dalam persiapan menyambut Tahun Baru 2023, kita bisa berimajinasi, seperti apa wajah Indonesiaku di tahun yang akan datang?
*Artikel ini pernah dipublikasikan di Thecolumnist.id, pada 27 Desmeber 2022.