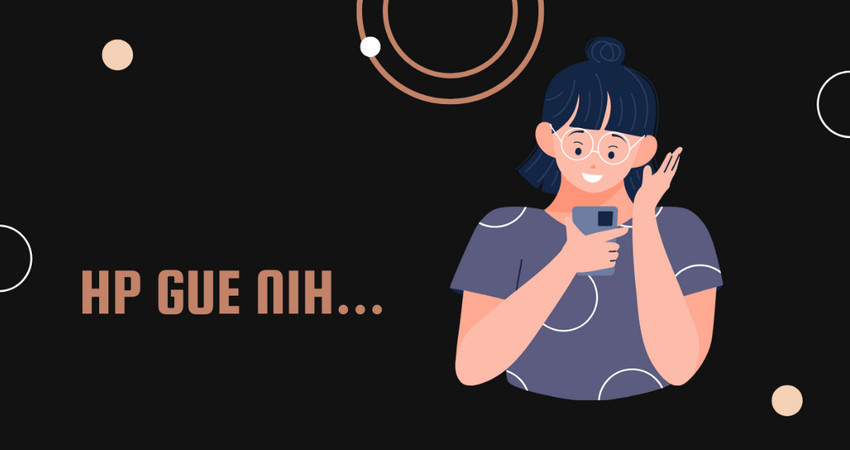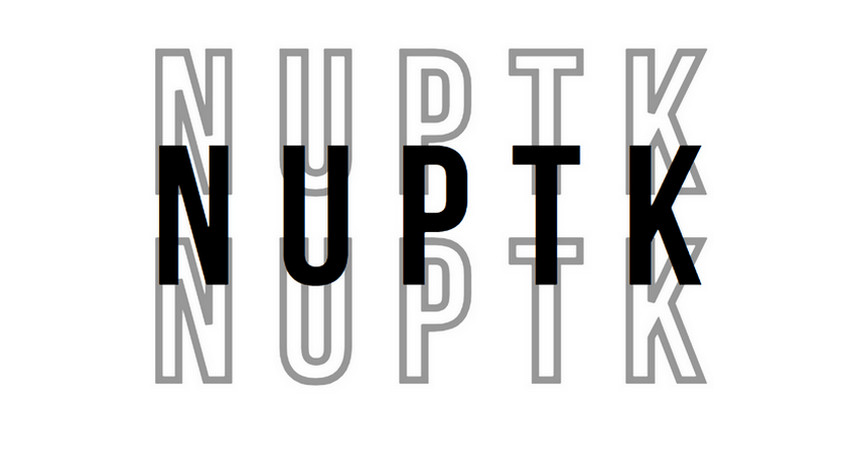Mau diakui atau tidak, alam bawah sadar kita saat ini telah digerogoti oleh media sosial dan konten-kontennya. Terumata anak-anak hingga keluarga muda yang hidup di kota dengan kemudahan akses internet. Tiap hari orang terus mengakses media sosial melalaui gawainya masing-masing. Entah terakit langsung dengan pekerjaan, maupun hanya sebagai hiburan.
Databooks (16/12/2022) mengemukakan bahwa menurut We Are Social, pada tahun 2022 masyarakat Indonesia menempati urutan kesepuluh dalam list pengakses media sosial terlama dalam sehari di seluruh dunia. Total pengguna media sosial di muka bumi mencapai 4,7 milyar pada awal Juli 2022.
Nigeria dicatat sebagai negara pengakses media sosial terlama dalam sehari yakni 4,11 jam per hari. Ia disusul Filipina, Ghana, Kolumbia, Afrika Selatan, Brazil, Argentina, Arab Saudi, dan Meksiko. Sementara Indonesia yang menempati urutan sepuluh mencatatkan waktu 3,2 jam per hari untuk menggunakan media sosial.
Coba perhatikan. Media sosial yang diproduksi negara maju malah paling banyak diakses di negara-negara berkembang. Apakah ini tanda positif atau negatif? Kita bisa mengulasnya di lain kesempatan dengan lain topik.
Di sini saya hanya ingin mengatakan bahwa kebiasaan mengakses dan menggunakan media sosial tanpa kita sadari turut mempengaruhi tindakan atau perilaku kita. Saya punya pengalaman konkret terkait hal ini.
Di kampus tempat saya berbagi ilmu, selain mengampu mata kuliah Dasar-Dasar Logika, saya juga menangani kelas fotografi. Saya sadar betul bahwa fotografi sebagai sebuah ilmu tidak cukup hanya dengan teori di kelas. Ia perlu praktik, bahkan harus lebih sering. Agak kurang pas kalau kelas fotografi lebih banyak di kelas daripada praktik lapangan.
Tahun 2013, ketika saya mengikuti kelas fotografi di Lembaga Pendidikan Jurnalistik Antara selama enam bulan, teori fotografi hanya diberikan pada dua pertemuan awal. Setelah itu, setiap hari saya harus menyempatkan waktu keliling ke berbagai sudut kota Jakarta untuk membuat foto. Sabtu, saat pertemuan masing-masing harus menampilkan hasil jepretannya. Bersamaan dengan itulah evaluasi dan teori tentang fotografi diperdalam. Pengalaman praktik-evaluasi itu, menurut saya, lebih efektif.
Maka, ketika saya dipercaya untuk memegang kelas fotografi saya mencoba untuk menerapkan model serupa. Teori hanya saya berikan di awal semester, sekitar tiga pertemuan, setelah itu kami memulai praktik. Kami sudah beberapa kali membuat foto, baik itu di kelas maupun di luar kelas. Kami mencoba beberapa tema, di antaranya interior, eksterior, makanan, hingga produk.
Sejak beberapa pekan lalu, saya meminta para mahasiswa untuk membuat foto produk makanan kemasan (food photography). Meraka boleh memilih makanan apa saja. Lalu, mereka juga saya tugaskan untuk membuat street photography. Lalu masing-masing mempresentasikan hasil fotonya di kelas.
Dari presentasi tersebut saya menemukan bahwa banyak mahasiswa mempresentasikan hasil foto yang ia jepret dalam format vertikal dengan aspek rasio rata-rata 9:16 (full portrait). Format pengambilan ini bahkan dipakai untuk memotret suasana kota saat senja atau kondisi jalanan yang ramai sehabis hujan.
Lazimnya dalam ilmu fotografi, jika kita hendak menyampaikan pesan ramai atau suasana kota pada sore hari, format foto yang dipakai hampir dipastikan horizontal dengan aspek rasio rata-rata 16:9. Kecuali untuk alasan-alasan khusus, foto tetap disajikan dalam bentuk vertikal meski pesan ramai dan luas yang ingin disampaikan dalam atau melalui sebuah foto.
Saya lalu bertanya-tanya, apa yang membuat para mahasiswa saya ini gemar sekali membuat foto dengan format vertikal daripada horizontal.Setelah dua kali presentasi di kelas baru saya temukan jawabannya.
Ternyata format vertikal dengan rata-rata razio 9:16 tersebut adalah format yang dipakai dalam tampilan media sosial TikTok, story dan reels Instagram dan Facebook, serta status WhatsApp. Pun rata-rata gawai yang kita genggam tiap hari memakai format ini.
Di sinilah baru saya sadari. Tampilan media sosial tersebut sudah berhasil memformat alam bawah sadar dan pikiran pengguna/pengaksesnya, termasuk para mahasiswa, sehingga setiap kali membuat foto dan video format itulah yang selalu digunakan.
Apalagi, buat mahasiswa yang ikut kelas fotografi karena mata kuliah wajib, bukan keinginan sendiri. Maka ia hanya membuat foto untuk memenuhi tugas, bukan untuk mengeksplorasi keterampilan fotografinya.
Ini baru soal format foto atau video. Belum lagi soal konten media sosial yang sudah hampir pasti ikut mempengaruhi cara berpikir, mental, hingga perilaku para pengaksesnya. Dengan rata-rata 3,2 jam sehari dihabiskan untuk mengakses media sosial, maka banyak sekali informasi tanpa sensor yang sampai kepada kita semua.
Maka, satu-satunya cara untuk bertahan di hadapan sumadera informasi yang hadir di media sosial ini adalah mawas diri dan tetap kritis, bahkan terhadap diri sendiri.
*Artikel ini pernah dipublikasikan di Kompasiana.com, pada 17 Desember 2022.